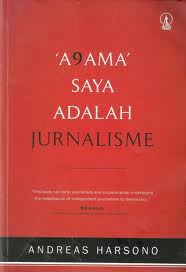 Satu
kutipan menarik yang dapat saya rangkum dari sebuah pernyataan terbuka
dari Andreas Harsono ketika saya beserta dua orang delegasi LPM Media
Sriwijaya lainnya mengikuti pelatihan manajemen web se-Sumatera. Saya,
Maman, dan Ardian mewakili LPM Media Sriwijaya untuk turut serta dalam
pelatihan yang digeber di Universitas Lampung ini. Sedikit deskripsi
mengenai Andreas Harsono. Pria berkulit putih yang merupakan alumnus
Harvard University ini seolah membuka cakrawala berpikir saya sebagai
seorang jurnalis. Sederhana sebetulnya. Tak ada yang istimewa dari
pernyataan seorang Andreas Harsono yang merupakan salah seorang jurnalis
besar di nusantara. Pernyataannya simpel namun syarat akan makna yang
dilontarkannya kepada partisipan PMWS 2011 cukup membuat otak saya
seolah bergelayut. Disela-sela presentasinya mengenai Citizen
Journalism, ia menyebutkan satu lontaran kalimat provokatif berupa
“DetikCom adalah contoh media yang tidak baik”. Perihal apa Andreas
melontarkan pernyataan demikian, hal tersebut merupakan refleksi atas
pertanyaan salah seorang peserta yang bertanya mengenai “Pagar Api”.
Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu “Pagar Api” ?
Satu
kutipan menarik yang dapat saya rangkum dari sebuah pernyataan terbuka
dari Andreas Harsono ketika saya beserta dua orang delegasi LPM Media
Sriwijaya lainnya mengikuti pelatihan manajemen web se-Sumatera. Saya,
Maman, dan Ardian mewakili LPM Media Sriwijaya untuk turut serta dalam
pelatihan yang digeber di Universitas Lampung ini. Sedikit deskripsi
mengenai Andreas Harsono. Pria berkulit putih yang merupakan alumnus
Harvard University ini seolah membuka cakrawala berpikir saya sebagai
seorang jurnalis. Sederhana sebetulnya. Tak ada yang istimewa dari
pernyataan seorang Andreas Harsono yang merupakan salah seorang jurnalis
besar di nusantara. Pernyataannya simpel namun syarat akan makna yang
dilontarkannya kepada partisipan PMWS 2011 cukup membuat otak saya
seolah bergelayut. Disela-sela presentasinya mengenai Citizen
Journalism, ia menyebutkan satu lontaran kalimat provokatif berupa
“DetikCom adalah contoh media yang tidak baik”. Perihal apa Andreas
melontarkan pernyataan demikian, hal tersebut merupakan refleksi atas
pertanyaan salah seorang peserta yang bertanya mengenai “Pagar Api”.
Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu “Pagar Api” ?Bagi kalangan jurnalis, istilah pagar api bukan barang baru yang mampir ke telinga si kuli tinta. Utamanya pers mahasiswa, pagar api adalah konotasi bagi sebuah layout grafis media online yang memisah batas secara tegas antara berita dan iklan. Antara idealisme dan profesionalisme. Jadi, si-penulis buku yang mengelaborasi sebuah pemikiran kreatif berbalut akidah jurnalistik “Agama Saya adalah Jurnalisme” itu menerangkan betapa bagi seorang jurnalis itu utamanya adalah berpikir merdeka. Relavan dengan jargonnya Teknokra “Tetap Berpikir Merdeka” bukan tanpa alasan kenapa sang empunya argumen berkata demikian, hal tersebut merupakan refleksi semakin tereduksinya permainan warna jurnalistik oleh pigura duniawi yang tidak artistik.
Kecenderungan media (sekarang) yang orientasinya bisnis-sentris mengindikasikan betapa esensi dan semangat seorang jurnalis itu semakin runtuh. Kegamangan media terhadap sejumlah ekspansi bisnis membuat tuntutan terhadap media semakin menyelekit. Media dituntut untuk tetap mengedepankan kaedah jurnalistik yang berlaku umum ketimbang memproporsikan kebutuhan finansial media yang semakin kompetitif dimakan zaman. Media yang diharapkan masyarakat adalah pemberitaan yang aktual, faktual dan terpercaya. Bukannya malah menjadi wahana baru bagi pebisnis dalam memasarkan produknya lewat media. Bak pribahasa ada gula ada semut, media sekarang menjadi seperti syurga baru bagi pengusaha. Hal ini sempat diulas Andreas Harsono yang mendeskripsikan 9 elemen jurnalistik.
Berangkat dari pemikiran Andreas, reformasi media sudah selayaknya digalakkan. Saya teringat dengan kampanya tim Cipta Media Bersama yang pernah menyambangi FH Unsri untuk memberikan semacam sosialisasi dan edukasi bagi insan pers mahasiswa yang ideal. Antara lain, kesetaraan media, advokasi media, dan kita butuh pembela.
Kekeliruan dan tantangan yang paling besar bagi insan pers secara kontekstual masih berada pada bias ideologi dan pemahaman. Andreas Harsono memaparkan secara eksplisit betapa insan pers saat ini menghadapi dilema antara idealisme dan profesionalisme. Kesalahan mendasar yang secara gamblang dapat kita ketemukan dalam pemberitaan yang saban hari menghiasi layar kaca dan headline media cetak nasional mengerucut pada pemberitaan yang tidak seimbang, memberitakan kesedihan, dan berakar pada adagium bad news is a good news. Pemaknaan bahwa berita yang sedikit dibumbui ‘penyedap’ menjadi corong media cetak nasional yang semakin besar seolah membuat ruang gerak jurnalis idealis semakin sempit. Sudah selesai sampai disitu ? belum jawabanya. Jurnalis kita masih berada pada dua bias. Bias agama dan bias Indonesia. telaah subjektif yang sedikit member nuansa edukatif pemikiran bahwa jurnalis kita menghadapi tantangan dalam pewartaanya. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim kerap membuat wartawan yang seiman meluputkan diri dari perhatian masyarakat dunia tentang kedok dibalik insania agamanya. Jurnalis terkadang menghadapi dilemma diantara seabrek fakta dan realita yang tengah menghadap didepan matanya. Namun, lagi-lagi bias agama dan rasa ketidak manusiaan harus disingkirkan agar agama sendiri tidak di jadikan sebagai kambing hitam. Contoh kasus, pembantaian warga Ahmadiyah di Cikeusik yang mengundang perhatian media internasional seperti CNN, NBC dll justru tak diminati secara serius dan ekslusif oleh wartawan lokal. Wartawan lokal cenderung main aman dalam memposisikan dirinya sebagai seorang jurnalis dan agamis. Perbedaan paling gambling adalah ketika wartawan nasional dan wartawan internasional meliput kasus yang sontak membuat gaung Bhinneka Tunggal Ika terusik. Andreas Harsono menjelaskan hal itu kepada saya betapa sebenarnya media-media nasional mengalami segregasi pemikiran dengan media internasional. Lantas, mestikah kita menjadi seorang atheis dan apartis untuk menjadi seorang jurnalis idealis ? tentu saja tidak. Yang dibutuhkan tentunya hanya keberanian. Berani dalam mengambil sikap yang tidak berani diambil oleh orang lain. Berani dalam berbicara ketika orang lain bungkam dan diam seribu bahasa. Berpikir merdekalah, karena itu hak kita. Hak politik yang diberikan Negara kepada kita mengapa kita tidak menikmatinya. Tetap Berpikir Merdeka !







0 comments:
Posting Komentar